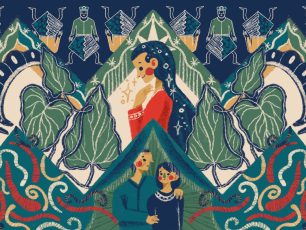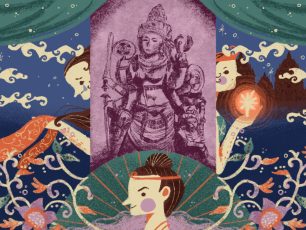Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri raja yang cantik jelita dan berhati mulia bernama Putri Mandalika. Pesonanya memikat hati banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang berlomba-lomba ingin meminangnya. Untuk menemukan petunjuk tentang jodohnya, sang putri memutuskan melakukan tapa penyucian diri.
Setelah masa tapa selesai, Putri Mandalika mengundang seluruh pelamar untuk berkumpul di Pantai Seger—yang kini dikenal sebagai Pantai Kuta Lombok. Pada hari yang telah ditentukan, ia tampil anggun mengenakan busana sutra dan berdiri di atas Bukit Seger bersama para pengawalnya. Di sana, ia menyampaikan keputusan yang mengejutkan: menerima semua lamaran demi menjaga kedamaian dan persatuan pulau.
Dengan hati yang berat, Putri Mandalika pun menjatuhkan diri ke laut dan hanyut ditelan ombak. Meski seluruh orang mencarinya, tubuh sang putri tak pernah ditemukan. Sebagai gantinya, muncul cacing laut berwarna-warni yang disebut nyale, yang diyakini sebagai jelmaan sang putri yang rela berkorban demi rakyatnya.
Terinspirasi dari kisah pengorbanan Putri Mandalika, masyarakat Lombok menggelar Upacara Nyale atau Bau Nyale setiap tahun. Tak hanya dalam bentuk ritual, nilai-nilai keberanian, kecerdasan, dan keteguhan sang putri juga dituangkan dalam motif kain batik yang khas. Motif tersebut menjadi simbol perempuan yang kuat dan bermartabat.
Kain ini dinamai “sasambo,” akronim dari tiga suku utama yang mendiami wilayah Nusa Tenggara Barat: Sasak, Samawa, dan Mbojo.
Kain ini dinamai “sasambo,” akronim dari tiga suku utama yang mendiami wilayah Nusa Tenggara Barat: Sasak, Samawa, dan Mbojo. Ketiganya hidup di dua pulau besar, yakni Lombok dan Sumbawa, dengan latar adat dan budaya yang berbeda-beda. Meski demikian, semangat untuk bersatu mendorong mereka menciptakan sebuah warisan budaya bersama melalui karya batik yang mencerminkan keberagaman dan keharmonisan.
Sejarah pembuatannya masih tergolong baru. Dorongan untuk melahirkan identitas lokal muncul setelah UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya dunia. Pemerintah daerah pun mulai menggagas batik khas NTB sebagai upaya pelestarian sekaligus kebanggaan daerah.
Karya bermotif sasambo pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 2010. Sejak itu, berbagai kebijakan mendukung penggunaannya—mulai dari kewajiban mengenakan batik sasambo bagi pegawai negeri hingga menjadikannya seragam di beberapa sekolah. Kegiatan membatik pun dikenalkan ke kalangan pelajar, seperti di SMKN 5 Mataram dan sejumlah pondok pesantren di Lombok Barat.
Akar budaya batik ini tertanam di tanah Jawa. Konon, tradisi membatik dibawa oleh Kerajaan Majapahit saat melakukan ekspedisi ke Kerajaan Selaparang di wilayah Nusa Tenggara. Meski begitu, praktik membatik tidak berkembang pesat karena masyarakat setempat lebih akrab dengan pembuatan kain tenun. Namun jejaknya masih tampak, antara lain pada capuq, ikat kepala khas NTB yang dihiasi motif batik.
Proses pengerjaan batik dilakukan secara tradisional, mengandalkan keterampilan tangan untuk menciptakan pola, motif, hingga pewarnaan.
Teknik pembuatannya sebenarnya serupa dengan batik dari daerah lain. Perbedaannya terletak pada tahap awal: kain yang digunakan harus ditenun terlebih dahulu. Hal ini mencerminkan kuatnya tradisi menenun yang telah lama hidup di Nusa Tenggara Barat.
Proses pengerjaan batik dilakukan secara tradisional, mengandalkan keterampilan tangan untuk menciptakan pola, motif, hingga pewarnaan. Salah satu tahapan yang menarik adalah proses pelepasan lilin—menggunakan potongan besi panas yang ditempelkan ke kain untuk membebaskan area tertentu dari warna—sebuah teknik yang menjadi ciri khas tersendiri dalam pengerjaannya.
Batik sasambo memiliki empat motif utama yang menjadi ciri khasnya, yaitu motif sasambo, mada sahe (mata sapi), kakando (tunas bambu), dan uma lengge (rumah adat). Setiap motif menampilkan ragam hias dan kombinasi warna yang unik. Motif mada sahe, misalnya, menampilkan hiasan mata sapi dengan latar kain hitam serta pola wajik dan zig-zag. Sementara itu, motif kakando memadukan garis dan bunga dengan dominasi warna merah marun. Motif uma lengge menggambarkan rumah adat dengan sentuhan warna hitam dan oranye yang kuat.
Motif-motif utama ini sering dipadupadankan dengan ragam hias pengisi, tergantung pada kekhasan budaya masing-masing etnis. Sebagai contoh, motif uma lengge bisa dilengkapi dengan elemen-elemen khas seperti untaian padi atau tarian tradisional buja kadanda dan mpa’a manca—tarian yang biasanya dipentaskan sebagai bentuk doa restu dan permohonan keselamatan sebelum berjuang atau berperang.
Meski tradisinya belum setua batik dari Pulau Jawa, batik sasambo berkembang pesat.
Meski tradisinya belum setua batik dari Pulau Jawa, batik sasambo berkembang pesat. Para perajin terus menggali inspirasi dari kekayaan budaya dan alam sekitar untuk menciptakan corak baru yang khas. Beberapa di antaranya adalah motif kelotok sapo (gantung leher sapi), rumah panggung, lumbung raja Bima, kerang, dan daun bebele—semuanya mencerminkan identitas lokal yang kuat dalam tiap helai kain.
Motif batik sasambo yang paling terkenal adalah motif kangkung, berpadu warna merah dan kuning keemasan yang menawan. Motif ini terinspirasi dari tanaman menjalar kangkung yang banyak tumbuh di Lombok dan menjadi bahan utama dalam masakan khas daerah, yaitu pelecing kangkung.
Corak dan warna memang menjadi pembeda utama batik dari setiap etnis. Di Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok menonjolkan motif bunga, dedaunan, unsur kesenian daerah, hingga representasi monumen. Sementara itu, Pulau Sumbawa lebih memilih motif yang mencerminkan identitas budaya dan etnis setempat.
Tak hanya pada motif dan warna, keunikan batik NTB juga terletak pada bahan kain yang halus serta sentuhan artistik yang rumit. Nilai jualnya bisa mencapai jutaan rupiah, sebanding dengan proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian tinggi dan waktu yang tidak singkat.
Meski belum begitu dikenal luas, batik khas NTB telah menjadi bagian penting dalam memperkaya khazanah budaya Indonesia. Keberadaannya turut mempertegas eksistensinya sebagai bagian dari warisan budaya dunia.