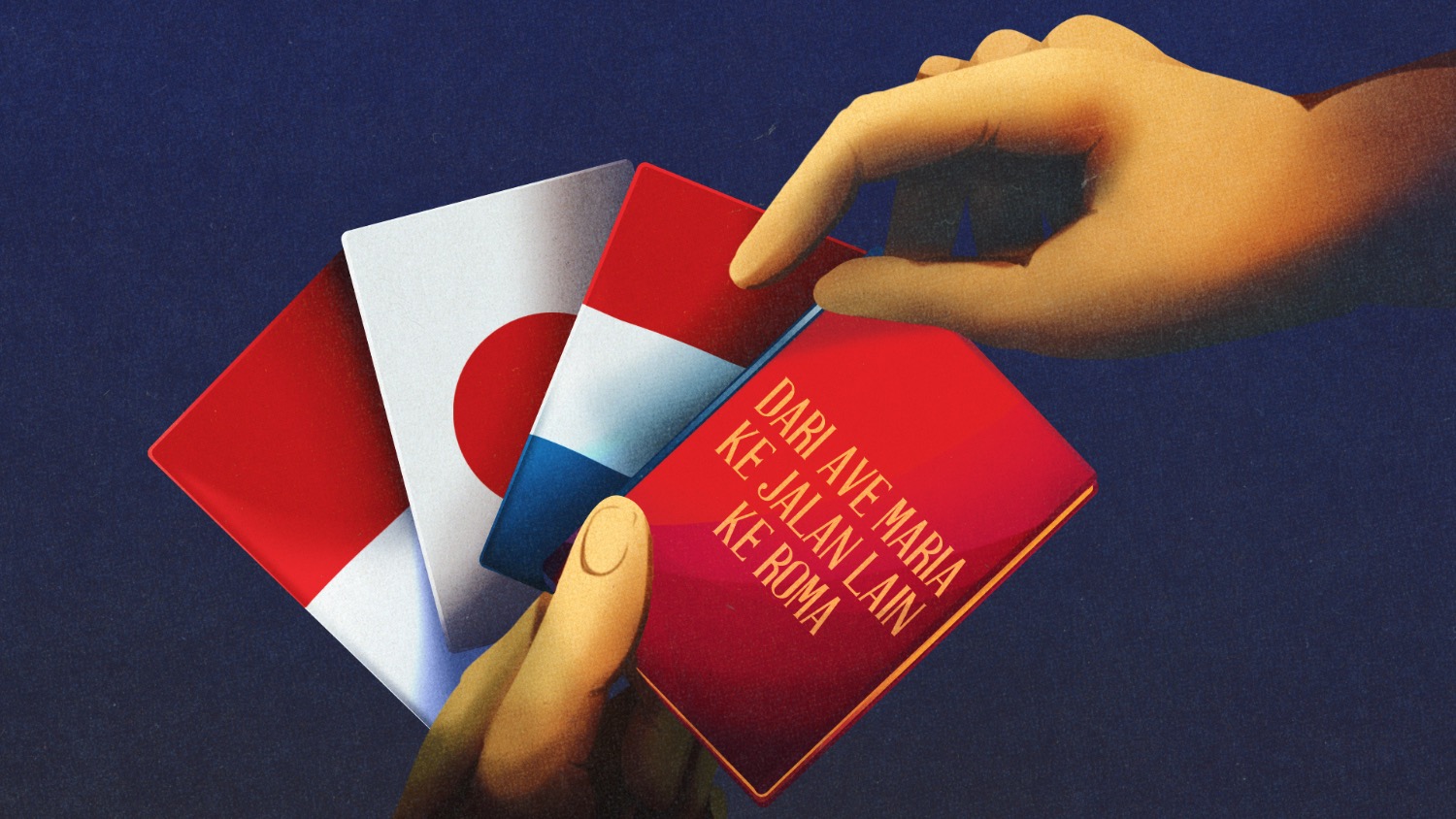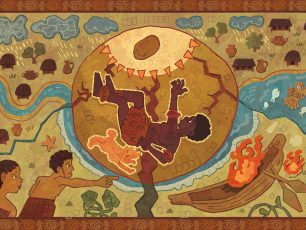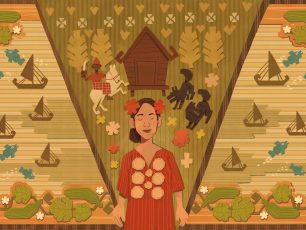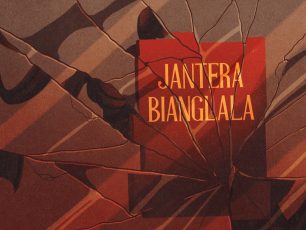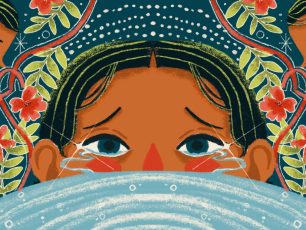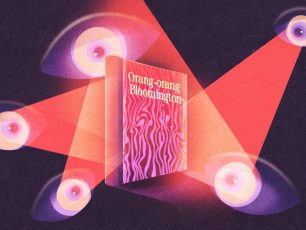Realisme yang membingkai kisah kehidupan rakyat Indonesia pada masa perjuangan dianggap sebagai penanda kelahiran sastrawan Angkatan 1945. Tak melulu puitis dan romantis, para penulis Angkatan ’45 lebih mengandalkan realitas kehidupan yang apa adanya, mengedepankan penggambaran sisi kejiwaan karakter, dan cenderung menggunakan gaya ekspresif mengalir yang terkadang terasa seperti gaya penulisan stream of thoughts (pemikiran dan perasaan karakter yang mengalir di sepanjang cerita).
Chairil Anwar kerap dipandang sebagai sosok utama pujangga Angkatan ’45 berkat kumpulan puisinya Aku Ini Binatang Jalang. Namun, penulis Idrus-lah yang didapuk oleh banyak pengamat sastra sebagai pelopor gaya penulisan yang secara kental memadukan nuansa realisme dan nasionalisme.
Secara langsung maupun tidak langsung, penulis asal Padang itu menggantikan gegap gempita semangat perjuangan dengan kesuraman kehidupan wong cilik yang menjadi korban dari aksi perjuangan. Ia jarang menuliskan aksi peperangan secara rinci (kecuali dalam satu cerita). Namun, ia lebih fokus pada dampak pascaperang—seperti perubahan status sosial, melonjaknya harga pangan, dan rasa curiga terhadap rekan sebangsa. Peperangan dan pengaruh asing di Tanah Air jarang digambarkan secara eksplisit, tetapi lebih ditekankan pada dampak yang dirasakan.
Buku kumpulan cerpen Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma (1948) karya mantan redaktur Balai Pustaka ini terdiri dari 11 cerpen dan 1 sandiwara. Dalam tiga babak—Zaman Jepang, Corat-Coret Bawah Tanah, dan Sesudah 17 Agustus 1945—kumpulan cerpen ini mengangkat kekisruhan dan kelabilan situasi hidup rakyat Indonesia pasca-Kemerdekaan, saat Jepang menduduki Indonesia.
Rangkaian Kisah Tiga Babak
Dibuka dengan cerita Ave Maria, novel terbitan Balai Pustaka ini memiliki alur yang lebih ringan dan sedikit unsur romantisme dibandingkan rangkaian cerpen setelahnya. Gaya bertutur cerita Ave Maria menggunakan flashback, di mana tokoh utama, Zulbahri, bercerita tentang masa lalunya ketika ia harus meninggalkan istrinya, Wartini, untuk bergabung dengan tentara Jepang.
Zulbahri pun merelakan adiknya, Syamsu, yang notabene merupakan mantan kekasih Wartini, untuk mengambil alih posisinya di rumah. Meski ringan, tapi Ave Maria bisa dilihat sebagai alegori tentang orang-orang yang mesti mengorbankan kepentingan keluarga demi ikut berperang. Di pengujung cerita, Zulbahri meninggalkan pesan, “Ini adalah sebagai pembayaran utangku kepada tanah air yang sudah sekian lama kulupakan karena mengingat kepentingan diri sendiri.”
“Ini adalah sebagai pembayaran utangku kepada tanah air yang sudah sekian lama kulupakan karena mengingat kepentingan diri sendiri.”
Sandiwara Kejahatan Membalas Dendam menghadirkan sosok pengarang bernama Ishak yang merasa hidupnya terancam setelah ia menerbitkan cerita kritis tentang kehadiran Jepang. Meski alur ceritanya agak rumit dan berbelit-belit—melibatkan ayah kekasih yang tidak menyetujui hubungan mereka, seorang nenek dukun, dan seorang kawan dokter yang ternyata memiliki niat jahat—akhir ceritanya berakhir optimis dan berusaha menjembatani aspirasi generasi tua dan muda. “Demikianlah hendaknya semangat pengarang Indonesia semua. Tidak ada kertas, tulis di mana saja. Jangan pikiran terbelenggu oleh yang kecil-kecil,” ujar satu tokoh.
Selanjutnya, suasana hidup tak menentu yang sarat keluhan pada zaman Jepang, dijadikan benang merah dalam babak Corat-Coret Bawah Tanah. Dimulai dengan cerita Kota Harmoni, dengan gaya ringkas dan realistis, Idrus menghadirkan sepenggal kisah hidup beberapa warga kota dari berbagai kelas sosial dan etnis melalui gambaran suasana trem yang sesak.
“Jangan banyak omong. Sekarang kemakmuran bersama, bukan Belanda,” kata seorang Tionghoa dengan ketus kepada nona Belanda yang mengeluh karena dia membawa terasi di kelas satu. Seorang lelaki Indonesia berdestar Jawa dan bersepatu Inggris pun mengaduh kepada kondektur atas lamanya waktu perjalanan dan kereta yang begitu sesak, hingga penumpang terpaksa berdiri di tangga (keluhannya tidak dihiraukan oleh kondektur). Kemudian, seorang perempuan gemuk terdengar ikut mengeluh, “Zaman susah sekarang. Tahun dua puluh susah juga, tapi tidak sesusah sekarang.”
Sejalan dengan Kota Harmoni, cerita pendek Oh … Oh … Oh! juga mengambil latar di atas kendaraan, yaitu kereta api dengan rute Sukabumi–Jakarta. Penggambaran kesenjangan sosial kembali ditampilkan, ketika orang dengan status sosial lebih tinggi diberikan kemudahan dalam membeli karcis.
Suasana tegang menyelimuti perjalanan di kereta. Segerombolan anak muda Indonesia, anggota Keibodan (pembantu polisi zaman Jepang), naik dan merampas kantong-kantong berisi beras para penumpang. Saat seorang anak muda berkaki satu (yang hendak merantau ke Jakarta untuk mengemis) jatuh dari kereta dan tewas, seorang penumpang melihatnya sebagai akhir yang lebih baik. “Aku lebih senang melihat ia mati begitu daripada melihatnya mati di pinggir Kali Ciliwung di Jakarta nanti.”
Cerita Jawa Baru lebih berfokus pada kemelaratan masyarakat. “Orang-orang tidak pandai menangis lagi, mereka hanya mengeluh. Setiap orang mengeluh karena kesusahan hidup. Beras sudah tiga rupiah satu liter. Di mana-mana orang berbicara tentang beras, kesusahan hidup, dan setiap orang menyalahkan Nippon.” Cerita bernada satir ini memang lebih vokal dalam mengkritik ketidakadilan Jepang, terutama soal alokasi pangan. Seperti yang terlontar dari kekesalan seorang warga, “Tokyo letaknya di utara, jauh sekali dari Pulau Jawa, tetapi jika Tokyo memerlukan beras, menjadi dekat sekali dengan Pulau Jawa”.
“Tokyo letaknya di utara, jauh sekali dari Pulau Jawa, tetapi jika Tokyo memerlukan beras, menjadi dekat sekali dengan Pulau Jawa”.
Pasar Malam Zaman Jepang menciptakan suasana pasar yang menjadi sumber hiburan bagi rakyat kecil. Namun, hiburan tersebut kadang membawa kesialan. Ironi ini tergambar dalam cerita tentang seorang pria kurus yang selalu kalah bermain rolet. Ia rela menjual semua pakaiannya hingga telanjang demi bisa terus bermain. Tanpa mereka ketahui, pasar malam tersebut sebenarnya merupakan sumber pemasukan uang bagi serdadu Jepang, “Obat mujarab untuk memberantas inflasi.”
Cerita Surabaya dan Jalan Lain ke Roma menjadi penutup babak Setelah Agustus 1945. Novelet Surabaya, yang diterbitkan terlebih dahulu, berkisah tentang situasi pasca-Kemerdekaan yang menegangkan dan dampaknya terhadap mentalitas manusia.
Terjadi perang berskala kecil antara koboi (pasukan Sekutu) dan bandit (pemuda-pemuda Indonesia), dan kedua pihak sama-sama garang. “Pemakaian pikiran menjadi berkurang, orang-orang bertindak seperti binatang dan hasilnya memuaskan. Orang tidak banyak percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan baru datang dan namanya macam-macam: bom, mitraliur, mortir.” Dan bandit-bandit itu pun kian lekat dengan revolver dan pisau belati yang mereka miliki.
Suasana sengit juga sering menimbulkan kecurigaan antar orang Indonesia sendiri. Ketika sekelompok pemuda melihat seorang perempuan mengenakan pakaian dengan elemen warna merah, putih, dan biru, ia dituduh sebagai mata-mata musuh dan dipukuli. Padahal, mereka salah mengidentifikasi warna. “Saudara, Saudara, berhenti memukul! Kita salah. Selopnya bukan biru, tetapi hitam.”
Cerita Jalan Lain ke Roma menjadi penutup. Dibandingkan dengan cerpen-cerpen lainnya, kisah ini terasa lebih imajinatif dan personal karena mengikuti perjalanan hidup satu tokoh utama bernama Open. Open mendapatkan nama tersebut dari orang tuanya berdasarkan sebuah kata yang pernah dilihat ayahnya dalam mimpi tentang Kota New York, yaitu openhartig (berhati terbuka). Sang Ibu menganggapnya sebagai semacam wahyu dan ia berharap anaknya tumbuh dewasa menjadi seseorang yang jujur.
“Open, engkau harus berterus terang dalam segala hal. Dengan jalan begitu engkau dapat memajukan dunia yang penuh dengan kebohongan ini.” Namun, terkadang, beban nama itu justru menjadi kutukan, terlebih lagi karena Open tumbuh menjadi orang yang cenderung polos dalam berpikir.
Saat dewasa, ia bekerja sebagai guru di sekolah. Suatu hari, ia diejek oleh anak-anak didiknya dengan sebutan “guru goblok” (pelesetan dari kata “golok”), setelah ia menceritakan bahwa istrinya pernah marah-marah dan mengejarnya menggunakan golok. Terdorong oleh suara hati, Open akhirnya memukul anak tersebut. Akibatnya, ia dipecat dari sekolah. Ia kemudian beralih menjadi mualim dan pengarang. Ketika kembali menulis, ia mengandalkan kejujurannya dalam bercerita, termasuk tentang situasi hidup pada masa itu, yang mengakibatkan ia sempat dipenjara oleh Jepang.
Belajar dari Sejarah
Keunggulan Idrus (1922–1979) sebagai penulis terletak pada realisme dan personalitas ceritanya, terutama dalam babak Corat-Coret Bawah Tanah. Kemungkinan besar, ia memang pernah berada dan bertemu dengan para penumpang trem Jakarta Harmoni.
Keunggulan Idrus (1922–1979) sebagai penulis terletak pada realisme dan personalitas ceritanya, terutama dalam babak Corat-Coret Bawah Tanah.
Dan nyatanya, ia memang berada di Surabaya ketika perang antara tentara Sekutu Inggris dan pasukan Mustopo meletus. Maka lahirlah novelet Surabaya, dengan gaya yang tak kalah apik dan realistis dari karya-karya Ernest Hemingway, penulis yang sering menampilkan realitas pahit perang.
Yang pasti, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, yang telah dicetak ulang sebanyak 28 kali,merupakan salah satu karya sastra Indonesia klasik yang penting untuk dibaca. Novel ini menyajikan sebuah cuplikan kisah sejarah Indonesia di bawah penjajahan Jepang yang penuh kesedihan dan kesengsaraan. Berbeda dengan Belanda yang lebih memanjakan kaum ningrat sebagai strategi untuk mengendalikan rakyat, Jepang justru melakukan kebalikannya: mereka membidik rakyat kecil.
Yang pasti, Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma, yang telah dicetak ulang sebanyak 28 kali,merupakan salah satu karya sastra Indonesia klasik yang penting untuk dibaca.
Dalam cerpen Heiho, seorang juru tulis bernama Kartono merasa sangat bahagia ketika terpilih menjadi anggota Heiho, yaitu tentara bentukan Jepang yang memberikan kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk berbakti kepada Tanah Air.
Kartono merasa status sosialnya akan meningkat, meskipun tugas utama anggota Heiho adalah sebagai pekerja kasar di garis depan. Istrinya yang tidak ingin dia menjadi anggota Heiho, memintanya untuk melempar seragam Heiho yang dia sebut “baju monyet”, lalu mencibirnya dengan berkata, “Kalau dalam rumah tangga Heiho itu dinamakan jongos, tolol!”
Apresiasi masyarakat terhadap kumpulan cerita pendek Idrus tampak dari cerita-ceritanya yang dimuat ke dalam buku lain. Heiho hadir dalam buku antologi Cerita Pendek Indonesia susunan Setyagraha Hoerip. Sementara itu, Kota Harmoni menjadi salah satu bahan pembelajaran sastra oleh Kakilangit, dan kemudian dimuat dalam buku Horison Sastra Indonesia 2 (Kitab Cerita Pendek). H.B. Jassin memuji buku ini memiliki kualitas sastra, berhasil menembus pasaran di tengah lautan terbitan pop, serta dapat menjadi salah satu pulau persinggahan yang nyaman bagi pencinta sastra.
Kumpulan cerita pendek Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma karya Idrus seolah-olah memberikan pesan kepada pembaca untuk belajar dari sejarah; belajar dari kenyataan kehidupan wong cilik pada masa lalu. Harapannya, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama.