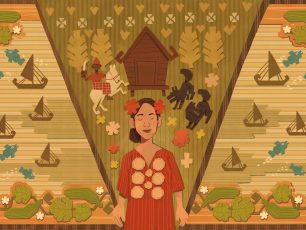Perahu-perahu dengan layar putih yang menjulang tinggi itu mulai mengarungi Laut Mandar. Bentuknya yang ramping membuat perahu-perahu ini melaju dengan cepat menyusuri lautan. Cadik yang khas, serta layar berbentuk segitiga menandakan bahwa perahu ini bukanlah perahu modern yang digunakan nelayan masa kini. Perahu-perahu ini adalah perahu tradisional suku Mandar, suku yang mendiami wilayah pesisir Sulawesi Barat. Orang-orang menyebutnya lopi sandeq atau perahu sandeq.
Dalam bukunya The Bugis, Christian Pelras menyebut orang Mandar sebagai pelaut ulung. Keunggulan suku Mandar, menurut Pelras, bukan berasal dari alat-alat yang canggih, melainkan dari kepiawaian mereka dalam menciptakan teknologi perikanan lokal yang dikembangkan sendiri. Teknologi-teknologi itu adalah rumpon (roppong) dan perahu sandeq.
Sandeq dari Tahun ke Tahun
Perahu sandeq merupakan hasil evolusi dari perahu-perahu tradisional seperti baqgo, palari, lambo, dan pakur, yang telah lama digunakan masyarakat suku Mandar untuk berlayar dan menangkap ikan di perairan Sulawesi Barat.
Perahu sandeq merupakan hasil evolusi dari perahu-perahu tradisional seperti baqgo, palari, lambo, dan pakur.
Bisa dibilang, pakur adalah cikal bakal sandeq. Perahu ini disebut sebagai warisan nenek moyang suku Mandar (suku-suku Austronesia) yang memiliki cadik dan layar. Pakur dulunya digunakan oleh pelaut Mandar untuk mengangkut kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan) ke Pulau Jawa, dengan bentuk yang lebih lebar daripada sandeq. Layar yang digunakan adalah sejenis tanjaq (segi empat) khas suku Austronesia. Inilah yang membuat pakur kurang lincah saat berlayar di lautan.
Setelah bersinggungan dengan teknologi pelayaran orang Eropa, pakur kemudian ditinggalkan oleh pelaut, nelayan, dan pembuat perahu suku Mandar. Ketika berlayar hingga ke Makassar, Surabaya, dan bahkan Tumasik (Singapura), pada masa penjajahan, para pelaut Mandar melihat layar segitiga kapal-kapal Eropa. Terinspirasi oleh inovasi tersebut, mereka kemudian mengembangkan layar segitiga itu untuk menciptakan perahu yang lebih baik, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Ridwan Alimuddin dalam bukunya Sandeq: Perahu Tercepat Nusantara.
Maka, sekitar tahun 1930-an, para pembuat perahu Mandar mulai menciptakan perahu sandeq (lopi sandeq) dengan layar segitiga atau layar massandeq, yang berarti runcing. Pakur pun perlahan-lahan ditinggalkan. Sejak itu, muncul pusat pembuatan perahu sandeq di Desa Pambusuang, Kecamatan Balanipa, dan Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar.
Spesifikasi Teknis sang Perahu Cepat
Penciptaan perahu ini tak lepas dari keinginan masyarakat Mandar untuk memiliki perahu yang cepat, cantik, dan kuat mengarungi lautan lepas. Kata sandeq sendiri dalam bahasa Indonesia berarti runcing. Sesuai arti tersebut, perahu sandeq memiliki bentuk haluan yang tajam. Ciri khas sandeq ada pada cadik atau sayapnya yang berjumlah dua, yang berguna untuk menjaga keseimbangan perahu saat dihantam ombak. Masyarakat Mandar menyebut cadik dengan kata baratang.
Ciri khas sandeq ada pada cadik atau sayapnya yang berjumlah dua, yang berguna untuk menjaga keseimbangan perahu saat dihantam ombak.
Cadik pada sandeq ditempatkan di bagian haluan dan tengah badan perahu. Awalnya, panjangnya sekitar 8 meter dengan lebar 70 sentimeter, namun kini telah berkembang menjadi 11 meter dan 60 sentimeter. Dengan lambung yang runcing dan cadik melengkung ke atas, kapal tradisional ini mampu menembus ombak dengan kecepatan 15–20 knot—menjadikannya perahu layar tercepat di Nusantara.
Proses pembuatannya menggunakan kayu pilihan dari Mamuju, seperti tippulu, palapi, dan maqdang, yang dikenal kuat dan ringan. Selain ketelitian teknis, masyarakat Mandar juga menjunjung nilai spiritual dalam setiap tahap, termasuk memilih waktu penebangan yang bertepatan dengan fase bulan purnama demi mendapatkan kayu berkualitas terbaik.
Ciri khas sandeq lainnya adalah cat putih, yang melambangkan kesucian dan kebersihan. Dulu, sandeq digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan, dengan tiga jenis utama: sandeq pangoliuntuk kawasan pesisir, sandeq paroppo untuk laut lepas, dan sandeq potangnga untuk menangkap ikan terbang di laut lepas. Namun, modernisasi menyebabkan para nelayan beralih ke kapal bermesin, yang lebih efisien dan mampu menampung hasil tangkapan lebih besar.
Ciri khas sandeq lainnya adalah cat putih, yang melambangkan kesucian dan kebersihan.
Meskipun perahu sandeq terakhir yang digunakan untuk menangkap ikan dibuat pada tahun 2000, sandeq tetap menjadi simbol penting bagi masyarakat Mandar sebagai warisan maritim dan semangat perlawanan terhadap keterbatasan. Sebagai bentuk penghormatan, setiap tahun diadakan perlombaan sandeq dengan jarak tempuh 480 km, yang menjadi ajang silaturahmi bagi para pelaut dari Sulawesi Barat dan Selatan. Perlombaan ini membuktikan bahwa dasar budaya bahari masyarakat Mandar, Bugis, dan Bajau memiliki kesamaan.