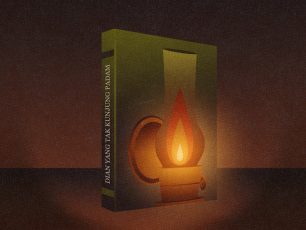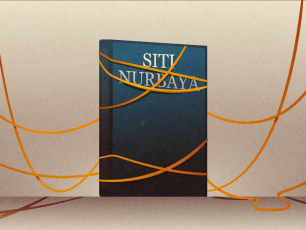Novel Indonesia Layar Terkembang merupakan salah satu karya sastra fenomenal di awal abad ke-20. Terbit pada 1937, novel roman karangan Sutan Takdir Alisjahbana ini jadi jembatan ke era pujangga baru yang mengusung semangat idealis dan kebebasan berpendapat. Uniknya, meskipun ditulis oleh seorang pria, narasi Sutan mengedepankan karakter wanita kuat berjiwa feminis.
Meskipun ditulis oleh seorang pria, narasi Sutan mengedepankan karakter wanita kuat berjiwa feminis.
Ada dua tokoh wanita dalam novel Layar Terkembang. Mereka adalah kakak-beradik Tuti dan Maria yang memiliki karakter bagai siang dan malam: Tuti lebih serius, tegas, mandiri, feminis; sementara sang adik adalah orang yang senantiasa ceria, luwes, keibuan, feminin. Dua oposisi kutub yang sebetulnya mengotakkan wanita dalam dua watak bertolak belakang yang stereotipikal—tanpa area abu-abu—mencerminkan persepsi perempuan di era saat novel Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka ini ditulis.
Cinta & Emansipasi
Narasi Novel Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisjahbana sepenuhnya fokus pada pergolakan kehidupan Tuti dan Maria. Tuti bekerja sebagai guru sekolah, dan di luar profesinya ia sangat aktif menyuarakan isu kesetaraan wanita di masa peran wanita hanya dituntut berada di sekitar dapur, sumur, dan kasur. Ia bergabung dalam organisasi wanita, Putri Sendra, dan kerap berorasi berapi-api dalam berbagai konferensi nasional. Meski banyak pria yang hendak menyuntingnya tapi Tuti menolak lantaran ia tak ingin nanti kebebasan dirinya dikekang dalam perannya sebagai istri.
Sementara Maria lebih menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang lebih membumi. Ia suka menikmati alam, tanaman berbunga, membaca cerita roman, dan memilin benang cinta yang ia harap kelak akan mengantarnya ke pelaminan. Ia menemukan pria idaman di sosok Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran, dan mereka pun memadu kasih. Tak lama, Maria dan Yusuf bertunangan. Sayangnya, jalan menuju pernikahan tersendat karena Maria sakit parah—situasi yang pada akhirnya mendorong Maria untuk mengajukan permintaan kepada sang kakak. Tuti pun harus mengambil keputusan sulit: apakah ia menuruti kemauan adiknya atau tetap berada di haluannya.
Bagian akhir dari novel Indonesia Layar Terkembang memang memiliki pelintiran alur yang mungkin tak terduga untuk sebagian pembaca. Bagi beberapa pembaca, mungkin progres narasi tersebut cenderung mundur ke belakang, terutama setelah mengikuti penokohan Tuti yang progresif dan idealis. Simak salah satu perkataan Tuti yang membekas dalam novel,
“hitam, hitam sekali penghidupan perempuan bangsa kita di masa yang silam, lebih hitam, lebih kelam dari malam yang gelap. Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri, perempuan hanya hamba sahaya, perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki, dengan tiada mempunyai hak. Setinggi-tingginya ia menjadi perhiasan, menjadi permainan yang dimulia-muliakan selagi disukai, tetapi dibuang dan ditukar apabila telah kabur cahayanya.”
Perempuan bukan manusia seperti laki-laki yang mempunyai pikiran dan pandangan sendiri, yang mempunyai hidup sendiri, perempuan hanya hamba sahaya, perempuan hanya budak yang harus bekerja dan melahirkan anak bagi laki-laki, dengan tiada mempunyai hak.
Mesti diakui bahwa sangat mengesankan mengetahui dialog bernuansa feminis tersebut merupakan perpanjangan pikiran Sutan Takdir Alisjahbana. Namun, itulah ideologi dari penulis aliran Pujangga Baru (yang juga termasuk Armijn Pane dan Amir Hamzah) yang tak sungkan mengadopsi nilai Barat yang modern dan liberal. Hingga saat ini belum diketahui inspirasi yang mendorong pria kelahiran kota Natal, Sumatra Utara, ini untuk menyisipkan tema feminisme pada cerita. Apalagi mengingat di tahun 1930-an pun peran perempuan di benua Barat masih reduktif.
Narasi Layar Terkembang bergulir secara horizontal, perpindahan plot terjadi secara organik dan linear, dijabarkan dalam tatanan bahasa modern (pada saat itu) dengan kecenderungan penggunaan rangkaian kata berbunga-bunga. Mayoritas kritisi novel Indonesia ketiga karangan Sutan Takdir Alisjahbana ini ditujukan pada penggambaran dan ideologi karakter yang dianggap sebagai inti kisah dari sang penulis.
H.B. Jassin dalam bukunya Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai I (1985) memberikan deskripsi pada Layar Terkembang sebagai “roman bertendensi”, karya sastra yang menyuarakan cita-cita, pemikiran, dan ideologi pribadi pengarang dengan memanfaatkan karakter-karakternya. Contoh kental ada dalam alokasi cerita Tuti yang bisa memuat satu halaman untuk konten orasi atau pemikiran sang pengarang, baik tentang isu gender atau nilai budaya Barat dan Timur.
Dalam ulasan yang berbeda dengan H.B. Jassin, pakar sastra Indonesia, A. Teeuw, dalam buku Sastra Baru Indonesia I (1980), menyatakan bahwa keunggulan Layar Terkembang terletak pada “dialog-dialognya yang hidup, serta watak tokoh Tuti yang merupakan watak yang amat penting dalam karya sastra Indonesia sebelum perang. Ia merupakan penjelmaan cita-cita Takdir yang sempurna: seorang gadis yang bebas, merdeka, dan yang dengan rela mengikat dirinya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang benar-benar harmonis dan memuaskan.”
Tokoh Tuti merupakan penjelmaan cita-cita Takdir yang sempurna: seorang gadis yang bebas, merdeka, dan yang dengan rela mengikat dirinya kembali kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang benar-benar harmonis dan memuaskan.
Tak dimungkiri Sutan Takdir Alisjahbana juga terkesan mengemas suatu esai dalam wujud novel roman. Suatu esai yang mengumbar semangat kemerdekaan, kebebasan, liberalisme, dan modernisasi; tak hanya melalui karakter Tuti tapi juga Maria dan Yusuf.
Pencinta Bahasa Indonesia
Sutan Takdir Alisjahbana, selain dikenal sebagai penulis dan perintis Pujangga Baru, juga tenar sebagai akademisi, politisi, dan pencinta bahasa Indonesia. Ia sempat menjabat sebagai dosen bahasa Indonesia di Universitas Indonesia (1946-1948), guru besar Bahasa Indonesia di Universitas Nasional (1950-1958), dan guru besar Tata Bahasa Indonesia di Universitas Andalas, Padang (1956-1958). Bersama Amir Hamzah dan Armijn Pane, ia mendirikan majalah Poedjangga Baroe dan pada 1945-1950 menjabat sebagai Ketua Komisi Bahasa Indonesia, di mana hasrat terpendamnya adalah mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan di Asia Tenggara, yang sayangnya tak pernah tercapai.
Kecintaan Sutan Takdir Alisjahbana pada bahasa Indonesia terpampang jelas pada tiap halaman Layar Terkembang. Bahkan bisa dibilang gaya bahasanya adaptif yang mengacu pada karakter: mendayu-dayu dan romantis kala bercerita tentang Maria, dan lugas dan membara dengan Tuti. Tak hanya narasi linear, tapi dalam novel ini Sutan juga menyajikan bentuk syair dan korespondensi surat-menyurat dalam menyampaikan cerita.
Layar Terkembang merupakan novel ketiga Sutan Takdir Alisjahbana setelah Tak Putus Dirundung Malam (1929) dan Dian yang Tak Kunjung Padam (1932), satu lagi novel karya Sutan yang menampilkan tokoh perempuan kompleks. Di sela-sela penulisan novel, ia juga pernah menerbitkan buku kumpulan puisi berjudul Tebaran Mega. Novel Layar Terkembang sendiri belum pernah diadaptasi menjadi film, yang mungkin dikarenakan kesulitan dalam mengadaptasi cerita yang cenderung pro-Barat.
Mungkin ada juga yang penasaran apa alasan di balik pemilihan judul Layar Terkembang. Peribahasa tersebut berasal dari kehidupan nelayan: “Lebih memilih tenggelam di lautan daripada harus kembali lagi ke pantai tanpa hasil.” Yang, dalam konteks novel Layar Terkembang, bisa ditafsirkan sebagai kegigihan seorang untuk meraih cita-cita. Karena sekali layar terkembang, jalan satu-satunya adalah untuk maju ke depan.
Karena sekali layar terkembang, jalan satu-satunya adalah untuk maju ke depan.