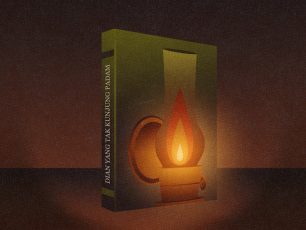Pantun merupakan satu di antara bentuk kesusastraan asli Nusantara. Pantun bagi masyarakat Indonesia ibarat sesuatu yang begitu dekat, tetapi kini terasa jauh ketika budaya populer makin menjadi primadona dalam industri hiburan.
Pantun ditaksir berasal dari tradisi Melayu yang sudah begitu kuat mengakar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Bisa jadi, penyebaran pantun sejalan dengan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia. Mungkin karena itu pula, jika dibandingkan dengan masyarakat di daerah lain, pantun bagi masyarakat Melayu sudah begitu kukuh menyatu dan sebagai media penting dalam menyampaikan nasihat berkenaan dengan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kata pantun sendiri berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti “penuntun”. Ada banyak jenis pantun berdasarkan isinya yang dikenal di Indonesia dan satu di antaranya yang sangat unik adalah pantun adat. Pantun adat mengandung petuah tentang adat istiadat dan kebudayaan. Gaya bahasa yang digunakan pun mengusung kearifan lokal asli tempat pantun tersebut berasal.
Kata pantun sendiri berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti “penuntun”.
Dalam bahasa Jawa, pantun adat dikenal sebagai parikan, dalam bahasa Sunda dikenal sebagai sisindiran, dan dalam bahasa Batak dikenal sebagai umpasa (baca: uppasa). Sementara, masyarakat Betawi juga menyebutnya pantun, meskipun bahasa yang digunakannya adalah bahasa Melayu Betawi.
Seni Pantun di Belitung
Salah satu daerah di Indonesia yang juga masih lekat dengan budaya dan kesenian pantun adalah Provinsi Bangka Belitung. Pantun merupakan salah satu jenis sastra lisan Bangka Belitung. Pelestarian budaya pantun pada masyarakat Bangka Belitung dapat kita temui misalnya pada acara pernikahan, agenda-agenda pariwisata, lomba berbalas pantun, dan acara budaya lainnya.
Salah satu ajang berbalas pantun masyarakat Belitung adalah campak. Kesenian campak menjadi hiburan masyarakat lokal, yang sampai hari ini masih mengundang keramaian dan kerap digelar hingga larut malam. Kesenian campak dapat dibagi menjadi dua, yakni campak darat dan campak laut.
Kesenian campak menjadi hiburan masyarakat lokal, yang sampai hari ini masih mengundang keramaian dan kerap digelar hingga larut malam.
Jika campak darat dijadikan tari pergaulan, maka campak laut yang dibawakan oleh masyarakat suku Sawang merupakan tari gembira yang diikuti dengan nyanyian dan dilakukan berpasang-pasangan. Biasanya, campak laut dilakukan hingga larut malam dan terkadang menjadi ajang mencari pasangan.
Dalam tari campak, biduan wanita memancing penonton pria yang bisa berpantun untuk maju ke atas panggung dan beradu pantun dengannya. Sambil menunggu, mereka menyanyikan lagu yang syairnya berisi pantun-pantun dalam bahasa Belitung.
Asal Usul Kesenian Campak
Seni campak merupakan salah satu kesenian tradisional yang masih bertahan di Belitung. Dulunya, kesenian ini sempat dianggap memiliki konotasi negatif, tetapi kini menjadi bagian yang penting dalam budaya lokal.
Ada berbagai teori mengenai asal-usul campak. Salah satunya adalah cerita nenek-nenek terdampar dari Vietnam yang menghibur diri dengan menari, yang kemudian berkembang menjadi kesenian campak. Ada pula yang meyakini bahwa campak berasal dari kata ‘mencampakkan uang’ atau karena moral yang tercampakkan. Beberapa sumber bahkan bercerita bahwa campak berasal dari Pulau Seliu, selatan Pulau Belitung; tempat nenek-nenek dari Vietnam menari setelah kapal mereka terdampar. Orang-orang itu konon asalnya dari Champa, Vietnam.
Namun, belum ada bukti pasti mengenai asal-usul campak ini. Meski begitu, campak telah menjadi bagian tak terpisahkan dari adat Melayu Belitung. Sebuah diskusi dalam acara Kelakar Seniman dan Budayawan Belitung di Gedung Nasional, Tanjungpandan, beberapa waktu lalu mengungkap sejumlah informasi menarik mengenai asal-usul seni campak serta transformasinya menjadi campak dangdut.
Kesenian campak biasanya diiringi oleh tiga alat musik, yaitu gendang panjang, tawang-tawang, dan piul atau biola. Namun, campak yang disaksikan masyarakat saat ini telah mengalami modernisasi dan dikenal sebagai campak dangdut. Sejarawan Belitung, Salim Yah, menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menarik perhatian penonton. Kombinasi antara campak dan bernyanyi dangdut dilakukan agar pertunjukan lebih diminati.
Kesenian campak biasanya diiringi oleh tiga alat musik, yaitu gendang panjang, tawang-tawang, dan piul atau biola.
Di masa lalu, campak seringkali dianggap kontroversial karena pakaian yang dikenakan penari tidak sesuai dengan norma pada masa itu, sehingga menyebabkan stigma negatif terutama pada tahun 1960-an. Pertunjukan campak biasanya dilakukan di tanah lapang dengan tikar sebagai alas bagi penari. Alunan musik menemani penampilan mereka yang sering kali menjadi sorotan bagi penonton, terutama dengan lantunan pantun yang kadang mengandung unsur merayu dan ‘nakal’. Bahkan, cara tradisional ‘nyawer’ campak dengan memberikan saweran uang membuatnya semakin dianggap kontroversial.