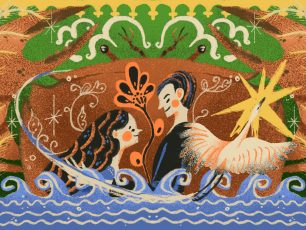Di tanah Jawa, ada banyak peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam. Salah satu situs berharga tersebut ada di Jawa Timur, tepatnya di Tuban. Tempat itu adalah kompleks peristirahatan terakhir Sunan Bonang, salah satu dari sembilan ulama besar yang tergabung dalam Wali Songo. Beliau aktif berdakwah memperkenalkan agama Islam sekitar abad 15 hingga 16 Masehi, dan tak lain adalah putra dari Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila.
Seperti layaknya seorang wali Allah, area makam Sunan Bonang masih ramai dikunjungi ratusan peziarah setiap harinya. Kompleks tersebut dibangun apik, demi menghormati Sunan Bonang dan kenyamanan para peziarah yang berganti-gantian melantunkan ayat suci Surat Yasin dan tahlil. Sebagian besar juga membacakan wirid surat Al-Fatihah sebanyak 50 kali, surat Al-Ikhlas 50 kali, dan shalawat 300 kali yang dikenal sebagai amalan yang diajarkan Sunan Bonang selama hidupnya.
baca : kampung dukuh
Selain tokoh besar yang terbaring di sana, keunikan makam juga berada pada kisah di baliknya. Karena sebenarnya terdapat perdebatan jika makam Sunan Bonang ada di dua tempat. Satu yang lainnya berada di Pulau Bawean, tempat Sunan Bonang berdakwah (sebagian lainnya mengatakan bertapa) untuk terakhir kali sebelum kemudian wafat karena sakit pada usianya yang ke-60 di tahun 1525.
Opini mengenai makam Sunan Bonang semakin berkembang hingga ada dua lokasi lain yang turut disebut sebagai makamnya yakni di Madura dan Lasem. Uniknya, semua tempat lainnya juga ramai dikunjungi peziarah. Lalu makam mana yang sebenarnya asli?
Kisah Singkat Sunan Bonang
Nama asli Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau adalah anak keempat, putra pertama, salah satu anggota Wali Songo lainnya yakni Sunan Ampel, dan kakak dari Sunan Drajat yang juga merupakan anggota Wali Songo. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam dari ayahnya. Kecerdasan dan latar belakangnya membuat Sunan Bonang menguasai banyak hal, termasuk ilmu fikih, usluhuddin, tasawuf, bela diri, arsitektur, hingga bidang seni dan sastra yang dipilihnya sebagai media dalam mengajar agama Islam.
Nama asli Sunan Bonang adalah Syekh Maulana Makhdum Ibrahim.
Ya, selain terdepan dalam urusan agama, Sunan Bonang juga pandai dan fleksibel. Beliau mempelajari terlebih dahulu hal apa yang menarik bagi masyarakat hingga akhirnya memilih menyebarkan agama Islam dengan bantuan alat musik pukul dalam orkes gamelan yang disebut dengan bonang. Alat musik ini dipukul sehingga mengeluarkan bunyi sebagai pengiring tembang yang beliau nyanyikan.
Begitu merdu suara yang dihasilkan, hingga memikat perhatian warga untuk mendengarkan tembangnya yang berisi kata-kata dari ajaran Islam. Seperti salah satu tembang yang terkenal hingga kini, Tombo Ati, yang secara harfiah berarti penyejuk jiwa. Beliau juga terkenal memiliki bakat dalam bidang sastra, terbukti dari hasil tulisannya berbentuk kitab ilmu tasawuf dengan tajuk Tanbihul Ghafilin setebal 234 halaman yang umum digunakan untuk mengajar agama kepada para santri.
Dalam berdakwah, Sunan Bonang dikenal dengan kebiasaan memadukan ilmu Islam dengan unsur kesenian dan kebudayaan yang kala itu sangat diminati warga, agar terdengar sederhana dan mudah dipahami. Para orang tua yang merasa cocok dengan caranya mengajar agama menitipkan anaknya untuk belajar dengan Sunan Bonang. Salah satu dari murid-muridnya ini adalah Sunan Kalijaga, yang kemudian mengikuti cara gurunya berdakwah dengan pendekatan kebudayaan.
Kisah Makam Sunan Bonang
Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam artikel ini, makam Sunan Bonang diyakini tak hanya ada satu melainkan dua, tiga, bahkan empat makam. Semuanya bermula dari kisah berpulangnya Sunan Bonang sendiri. Dikatakan bahwa di usia tuanya, Sunan Bonang meninggalkan pesantren di Tuban untuk kembali berkeliling daerah mengajar agama. Salah satu lokasi yang didatanginya adalah Pulau Bawean. Dalam perjalanannya ini, beliau jatuh sakit kemudian meninggal dunia.
Seperti yang disebutkan sebelumnya dalam artikel ini, makam Sunan Bonang diyakini tak hanya ada satu melainkan dua, tiga, bahkan empat makam.
Muridnya di Pulau Bawean beranggapan jika Sunan Bonang memilih Pulau Bawean sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, maka Sunan Bonang harus dimakamkan di Pulau Bawean. Sedangkan muridnya di Tuban menginginkan jenazah gurunya dikembalikan dan dimakamkan di Tuban. Akhirnya, beberapa murid dari Tuban datang ke Pulau Bawean untuk mengambil jenazah gurunya.
Jenazah pun dibawa ke Tuban, namun ada kisah warga mengatakan jika jenazah Sunan Bonang di Pulau Bawean masih ada. Yang berbeda, kain kafan yang digunakan jenazah tinggal satu lapis. Maka setelah dimakamkan di Tuban, ada pula yang meyakini jika makam di Bawean–ada dua lokasi di sana–juga adalah makam Sunan Bonang. Sedangkan makam di Lasem dan Madura adalah makam tokoh lain dengan jejak petilasan Sunan Bonang saat mengajar agama di sana.
Makam Sunan Bonang di Tuban
Dari semua makam yang disebutkan merupakan tempat peristirahatan terakhir sang wali Allah, ada satu yang paling populer dan telah mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai cagar budaya–penetapan ini tentu sudah melalui penggalian sejarah sebelumnya–yakni makam Sunang Bonang yang terletak di Dukuh Kauman, Kelurahan Kutorejo, Tuban. Tepatnya makam yang berada di sebelah Barat Masjid Agung Tuban.
Dari semua makam yang disebutkan ada satu yang paling populer dan telah mendapatkan pengakuan pemerintah sebagai cagar budaya yakni makam Sunang Bonang yang terletak di Dukuh Kauman, Kelurahan Kutorejo, Tuban.
Saat sampai, peziarah akan disambut gapura pertama dari tiga yang berdiri di dalam kompleks. Gapura pertama berbentuk regol, memiliki corak Hindu-Buddha yang menandakan peziarah memasuki lokasi yang suci, atau di dalamnya bersemayam seorang tokoh yang memiliki pengaruh sangat besar.
Selanjutnya peziarah disambut gapura kedua dengan bentuk paduraksa dengan hiasan piring yang dilengkapi ornamen bunga dan tulisan Arab. Di area ini juga terdapat Masjid Astana Bonang, yakni tempat Sunan Bonang dahulu sering menyepi untuk berdoa. Di sisi utara masjid, terdapat gapura ketiga yang juga berbentuk paduraksa dan dihiasi ornamen piring yang salah satunya bertuliskan nama empat khalifah Nabi Muhammad SAW yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Memasuki jalan setapak setelah gapura ketiga, peziarah akan menemui banyak makam saat menuju ke lokasi makam Sunan Bonang. Cungkup makam Sunang Bonang sendiri berada di tengah sebuah pendopo, tanahnya lebih rendah dibanding beberapa makam dan batu nisan di sekitarnya yang merupakan makam kerabat dan pengikut setia Sunan Bonang. Para peziarah biasanya akan duduk bersila di area sekitar makam–yang ditutupi tirai–untuk membaca doa. Mereka berharap mendapatkan berkah, dan lebih jauh lagi meminta petunjuk spiritual dari Allah melalui tokoh besar yang ada di dalam makam.
Sebagian yang sudah selesai berdoa juga dapat berkeliling sejenak di sekitar area makam di mana terdapat pendopo-pendopo berisi benda bersejarah (pendopo paseban, pendopo rante, dan pendopo tajuk), dan beberapa peninggalan Sunan Bonang saat dahulu beliau mengajar agama. Selain makam Sunan Bonang sendiri, ada 26 beda lain dalam kompleks ini yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.
Selain makam Sunan Bonang sendiri, ada 26 beda lain dalam kompleks ini yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya.
Pentingnya Makam Sunan Bonang
- Bukti Penyebaran Agama Islam: Sebagai bukti konkret dari kehidupan dan peran penting Sunan Bonang lsebagai salah satu tokoh sentral dalam penyebaran agama Islam di Jawa.
- Warisan Budaya: Makam ini menjadi saksi bisu perkembangan seni dan kebudayaan pada masa lalu.
- Spiritualitas dan Ziarah: Makam Sunan Bonang merupakan tempat yang dihormati dan dianggap suci oleh umat Muslim. Banyak orang datang untuk berziarah, berdoa, dan mencari berkah.
- Toleransi Agama: Sunan Bonang terkenal karena pendekatannya yang toleran dan inklusif terhadap agama-agama lain. Melalui penyebaran ajaran Islam yang toleran, Sunan Bonang membantu membangun hubungan yang harmonis antar pemeluk agama berbeda.
- Tempat Penelitian dan Pembelajaran: Kompleks makam Sunan Bonang menjadi lokasi penelitian dan pembelajaran bagi para akademisi, sejarawan, dan peneliti. Mereka mempelajari kehidupan Sunan Bonang, ajaran-ajarannya, serta pengaruhnya dalam penyebaran Islam di Jawa.
Dengan pentingnya makam Sunan Bonang, perlu ada perhatian dan upaya pelestarian dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai-nilai sejarah, budaya, dan spiritual yang terkandung di dalamnya tetap hidup dan diwariskan kepada generasi yang akan datang.